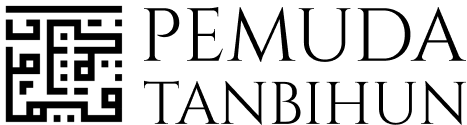Banyaknya kegiatan pengajian yang dilaksanakan di desa, tidak menjamin dan menjanjikan akan terciptanya masyarakat yang lebih baik. Hal ini, bukan berarti kita harus meninggalkan kegiatan pengajian dan menggantinya dengan kegiatan yang lain, agar tepat sasaran. Sebab, kegiatan tersebut masih diminati bahkan menjadi tradisi bagi masyarakat sebagai wadah untuk mengsyiarkan agamanya. Adapun kurang efektifnya kegiatan tersebut dalam mempengaruhi masyarakat ke arah yang lebih baik, alangkah baiknya kita jadikan masalah tersebut sebagai bahan untuk diuraikan dan dievaluasi dalam rangka mencari solusinya.
Pengajian, merupakan media dakwah secara lisan. Pada umumnya, kegiatan pengajian memfokuskan pada pendai atau tokoh yang berlabel kiai atau ustadz dalam memberikan ceramahnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi dan memotifasi masyarakat agar dapat menata kehidupan yang lebih baik.
Pemfokusan pada kiai panggung, dapat dilihat dari tingkat antusias masyarakat dalam menghadiri dan mengikuti jalannya pengajian, yang dipengaruhi oleh siapa yang akan mengisi acara inti yaitu maidzoh hasanah. Usaha dakwah melalui kegiatan pengajian, memposisikan seorang pendakwah panggung menempati tempat yang paling strategis dalam mempengaruhi hal-hal positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kiai panggung dalam kasus ini, menanggung beban tanggung jawab yang besar sekaligus menjadi kunci bagi terbukanya pintu hidayah bagi masyarakat.
Dari sini, kita dapat melihat bagaimana potensi kiai panggung dalam kegiatan pengajian sebagai usaha mempengaruhi masyarakat. Kemungkinan kurang efektifnya sebuah pengajian disebabkan oleh kiai panggung yang kurang profesional. Jika memang benar, bahwa kiai panggung adalah salah satu faktor yang menghambat kesuksesan acara tersebut, lantas bagaiman seharusnya kiai podium dalam menyampaikan ceramahnya?.
Syaikh Abdul Qadir Al Jailani dalam kitab Fathu Rabbany menukil perkataan Hasan Basry yang menyinggung tentang bagaimana memberi petuah kepada manusia, seperti berikut,[1]
عظ الناس بعملك و كلامك يا واعظا عظ الناس بصفاء سرك وتقوى قلبك ولا تعظهم بتحسين علانيتك مع قبح سريرتك
Artinya: Nasihatilah manusia melalui perilaku dan perkataanmu. Wahai penceramah, nasihatilah manusia dengan kebersihan dan ketakwaan hatimu, dan jangan menasehati mereka dengan kebagusan yang engkau perlihatkan bersamaan keburukan di hatimu.
Berpijak dari sini, seorang kiai panggung haruslah menasehati masyarakat melalui perkataan maupun perilaku dengan penuh ketakwaan hati. Idealnya kiai Panggung, sebelum menuturi dan menasehati masyarakat, ia sudah mengamalkan ilmunya dalam bentuk perilaku yang baik, kemudian menggunakan lisan untuk menasehati masyarakat. Perilaku dan perkataan yang lahir dari hati bersih penuh dengan ketakwaan, agaknya lebih diterima dan didengar oleh hati masyarakat, yang kemudian menjadi sebuah langkah awal untuk berbuat baik yang pada akhirnya kiai panggung pantas mendapat label rahmat bagi mukmin.
Ajakan secara lisan yang bersumber dari prilaku, merupakan sebuah komitmen seseorang atau kiai panggung dalam memposisikan masyarakat sebagai bagian dari tubuhnya. Pasalnya, ia menginginkan masyarakat untuk ikut merasakan nikmatnya berprilaku baik seperti yang sudah ia lakukan sendiri. Ajakan seperti ini adalah bentuk cinta kiai panggung terhadap masyarakat yang sekaligus mengindikasikan keutamaan iman kiai panggung. Agaknya, hal inilah yang diisyaratkan oleh hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al Haitamy dalam kitab Fathul Mubin, sebagai berikut;[2]
افضل الايمان ان تحب للناس ما تحب لنفسه
Artinya: Lebih baik-baiknya iman adalah engkau mencintai untuk manusia sesuatu yang engkau sendiri mencintainya untuk diri sendiri.
Oleh karena itu, seorang kiai podium dalam menjalankan dawahnya
melalui acara pengajian, harusnya didasari cinta terhadap masyarakat, bukan
didasari honor atau imbalan yang diberikan yang diterima dari masyarakat,
sebagai usaha agar tujuan dari acara pengajian dapat dicapai, yaitu terbukanya
pintu hidayah bagi masyarakat.
[1] Syaih Abdul Qadir Al Jailani, Fathu Rabbany. Hal, 95.
[2] Ibnu Hajar Al Haitamy, Fathul Mubin. Hal. 306.